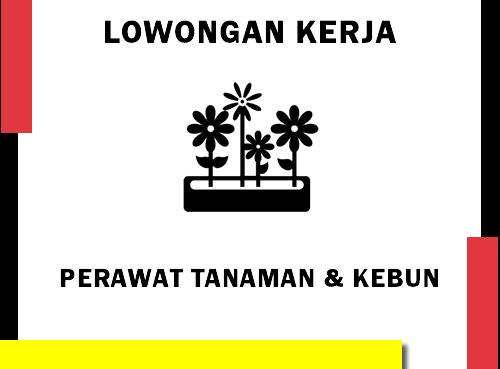Siapa sih yang tidak tahu Gunung Slamet? saya yakin banyak yang sudah tahu, apalagi yang biasa mendaki gunung
0k guys inilah kisah kami mendaki Gunung Slamet dari jalur pendaki Desa Gambuhan
Gema Tawa di Atap Jawa Tengah
Langit di atas Desa Gambuhan, Pemalang, berwarna nila pekat saat kami, sepuluh pendaki, merampungkan persiapan terakhir. Jarum jam baru saja melewati waktu Isya. Udara dingin yang khas pegunungan mulai menusuk tulang, namun semangat kami membara, lebih panas dari api unggun kecil di depan basecamp. Dipandu oleh Pak Marno, seorang juru jalan lokal yang wajahnya setenang malam itu sendiri, kami memulai pendakian menuju atap Jawa Tengah, Gunung Slamet.
“Ingat, jaga ucapan, jaga sikap. Kita hanya tamu di sini,” pesan Pak Marno sebelum kami melangkah masuk ke gerbang hutan. Kami mengangguk, meski dalam hati, rasa jemawa khas anak muda masih terselip.
Perjalanan dari basecamp menuju Pos 1 dan Pos 2 terasa berat namun lancar. Suara serangga malam dan gemerisik daun menjadi musik pengiring langkah kami. Canda tawa masih terdengar di antara napas yang terengah-engah. Namun, suasana mulai berubah drastis saat kami meninggalkan Pos 2.
Medan menjadi semakin terjal dan tak kenal ampun. Akar-akar pohon melintang seperti ular raksasa yang siap menjegal. Langit yang tadinya bersih kini tertutup awan kelabu. Tak lama kemudian, gerimis dingin mulai turun, membuat jalur tanah yang kami pijak menjadi licin dan berbahaya. Kami tiba di Pos 3 dalam kondisi basah kuyup dan kelelahan.
Di sinilah segalanya dimulai.
Kami beristirahat sejenak di bawah naungan pohon rindang, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, angin berembus jauh lebih kencang dari sebelumnya. Bukan sekadar angin gunung biasa. Angin ini menderu-deru, membawa hawa dingin yang terasa ganjil dan membuat bulu kuduk meremang. Ranting-ranting pohon berderak hebat seolah hendak patah.
Di tengah deru angin yang memekakkan telinga itu, sebuah suara lain ikut terbawa.
Awalnya samar, lalu semakin jelas. Suara tawa perempuan. Tawa yang melengking tinggi, tajam, dan penuh taraf. Suara itu seperti menari-nari bersama hembusan angin, datang dari segala arah namun tak berasal dari mana pun.
Hi-hi-hi-hi-hi…
Seketika, semua candaan lenyap. Kami membayangkan, saling berpandangan dengan mata membelalak ngeri. Wajah kami yang pucat pasi diterangi sorot headlamp masing-masing. Ini bukan suara manusia. Ini adalah suara yang selama ini hanya kami dengar dari cerita-cerita horor. Tawa si Kunti.
“Jangan menoleh! Jangan menunjuk! Teruslah berdoa dalam hati!” perintah Pak Marno dengan suara rendah namun tegas. Matanya menatap lurus ke depan, seolah-olah tidak mempengaruhi, meski kami bisa melihat rahangnya mendominasi.
Suasana menjadi sangat mencekam. Gerimis semakin deras, angin terus menderu, dan tawa itu tak kunjung berhenti. Rasanya seperti ada sosok tak kasat mata yang sedang mengawasi kami dari kegelapan, kegelapan perjuangan kami di tengah medan terjal dan cuaca buruk. Tak ada yang berani berpikir. Kami hanya bisa menunduk, mendekatkan barisan, dan melanjutkan perjalanan dengan jantung yang berdebar kencang, berharap segera lepas dari teror di Pos 3.
Perjuangan semalaman itu akhirnya terbayar saat kami mencapai puncak menjelang Subuh. Keindahan matahari terbit dari puncak Slamet menimbulkan kengerian yang kami alami. Namun, bayang-bayang tawa itu tetap melekat di benak kami.
Setelah puas menikmati pemandangan, kami memulai perjalanan turun. Pagi hari membuat jalur terlihat lebih jelas, dan suasana hati kami sedikit membaik. Kami berpikir bagian terburuk telah usai. Kami salah besar.
Saat melintasi area setelah Pos 3, tempat kami diteror semalam, sesuatu yang aneh terjadi. Jalur yang kami lewati terasa berbeda. Terlalu landai, terlalu bersih, dan anehnya sangat mudah untuk dilalui. Vegetasinya pun terasa lebih rapat dan asing.
“Kok memutarnya jadi enak gini ya?” celetuk salah satu temanku, Rian.
“Iya, nggak inget lewat sini malam,” sahut yang lain.
Kami terus berjalan tanpa curiga, seolah terhipnotis oleh kemudahan jalur itu. Langkah kami terasa ringan, dan pandangan kami hanya lurus ke depan. Pak Marno, yang biasanya berada di depan, entah kenapa kali ini berada di barisan tengah, wajahnya tampak berpikir keras.
Hingga salah satu dari kami yang paling belakang, Adi sambil berteriak.
“BERHENTI! SEMUANYA BERHENTI!”
Teriakannya yang panik menyentak kami dari lamunan aneh itu. Kami berhenti dan menoleh ke belakang. Adi menunjuk ke samping.
“Jalur aslinya di sana! Kita salah jalan!”
Kami semua berpaling ke arah yang ditunjuk Adi. Benar saja, sekitar lima meter di sebelah kiri kami, tersembunyi di balik semak belukar, adalah jalur pendakian yang sebenarnya. Jalur yang berbatu dan penuh akar, yang seharusnya kami lewati.
Lalu… jalur yang kami pijak ini apa?
Dengan perasaan ngeri, kami menoleh ke depan. Jalur ‘enak’ yang kami ikuti ini ternyata tidak menuju ke mana-mana. Hanya beberapa meter di depan, jalur itu berakhir. Berakhir di sebuah bibir jurang yang dalam dan menganga, tertutup kabut tipis.
Kaki kami gemetar. Lutut terasa lemas. Kami hanya beberapa langkah lagi dari kematian. Jika Adi tidak sadar dan berteriak, kami mungkin akan terus berjalan tanpa berpikir, satu demi satu, dan jatuh ke dalam jurang itu.
Pak Marno segera mengambil alih. Wajahnya pucat pasi. “Astaghfirullah…kita dibelokkan ,” desisnya. Ia segera memimpin kami membaca doa dan dengan hati-hati kembali ke jalur yang benar.
Perjalanan kembali ke basecamp dilalui dalam kebisuan total. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi canda. Yang ada hanya langkah-langkah cepat dan pandangan waspada. Kami sadar sepenuhnya, kami bukan sekedar mendaki gunung. Kami telah masuk ke dunia lain yang tak terlihat, dan kami beruntung bisa kembali dengan selamat. Gema tawa di Pos 3 dan jalur gaib jurang menuju menjadi pelajaran abadi: di hadapan keagungan gunung, manusia tak punya hak untuk merasa sombong.
Kisah di atas disadur dari kisah nyata, tetapi dengan nama-nama samaran.
terimakasih.